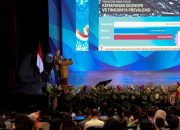detak.co.id, KOTA TANGERANG – Dalam beberapa peristiwa besar di Indonesia, sering terlihat pola komunikasi yang berulang. Kasus baru mencuat, publik segera memenuhi media sosial dengan tafsir, opini, dan spekulasi, sementara institusi baru menyampaikan informasi beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian.
Pada saat institusi akhirnya muncul, opini publik sudah terbentuk dan sulit diubah. Narasi telah diambil alih oleh komentar viral, potongan video, dan berita alternatif yang beredar jauh lebih cepat. Fenomena ini bukan sekadar soal kecepatan, tetapi soal siapa yang berhasil mengatur agenda perbincangan publik.
Teori agenda setting dapat menjelaskan pola ini. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Namun, di era digital, kekuatan itu tidak hanya dimiliki oleh media konvensional, tetapi juga oleh platform media sosial dan aktor-aktor di dalamnya. Ketika satu video viral memicu puluhan ribu komentar, ia otomatis menjadi agenda pembicaraan nasional. Masyarakat mengikuti alurnya, meskipun belum ada data lengkap. Di titik ini, institusi tertinggal karena ritme komunikasi mereka tidak sesuai dengan ritme informasi publik yang semakin cepat dan penuh tekanan.
Fenomena ini terlihat jelas pada banyak isu mulai dari konflik publik, skandal pejabat, hingga persoalan hukum. Orang pertama yang bicara di ruang digital sering lebih menentukan arah perbincangan daripada lembaga resmi. Sekali isu viral, publik tidak lagi menunggu klarifikasi institusi. Mereka membangun narasi sendiri, mengisi ruang kosong dengan opini dan analisis amatir yang terasa masuk akal karena muncul lebih cepat.
Ketika institusi akhirnya merilis pernyataan, publik sering menanggapinya dengan sinis, menganggapnya sebagai versi yang terlambat.
Fenomena ini juga dapat diamati dalam respons publik terhadap kunjungan sejumlah kader partai politik ke lokasi bencana banjir di Sumatera baru-baru ini. Kehadiran mereka di lapangan segera menjadi bahan perbincangan luas di media sosial, bahkan sebelum ada penjelasan resmi mengenai tujuan, konteks, atau bentuk bantuan yang disalurkan. Berbagai tafsir muncul secara bersamaan: sebagian melihatnya sebagai bentuk kepedulian, sementara yang lain menilainya sebagai manuver pencitraan.
Dalam situasi tersebut, perbincangan publik berkembang lebih cepat daripada klarifikasi institusional, sehingga agenda diskusi terbentuk terlebih dahulu di ruang digital, bukan di ruang informasi resmi. Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan yang secara formal bersifat sosial dapat dengan cepat dimaknai secara politis ketika komunikasi institusi tertinggal dari ritme spekulasi publik.
Salah satu pemicunya adalah fakta bahwa algoritma media sosial dirancang untuk mempromosikan konten yang paling memicu respons emosional. Ketika sebuah isu dimasukkan ke dalam pusaran algoritma, ia akan terdistorsi oleh interpretasi dan amplifikasi. Agenda perbincangan pun tidak lagi ditentukan oleh kepentingan publik, tetapi oleh kepentingan platform untuk mempertahankan atensi.
Dalam situasi seperti ini, institusi berada pada posisi sulit karena mereka harus menjaga akurasi, namun publik menuntut kecepatan. Akibatnya, institusi selalu tampak lamban meskipun sebenarnya sedang memeriksa fakta.
Agenda setting digital juga memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk makna secara kolektif tanpa menunggu data. Ketika banyak orang membicarakan suatu hal, hal itu terasa benar.
Ketika banyak orang marah, kemarahan itu terlihat sah. Mekanisme ini mendorong publik untuk menganggap perbincangan viral sebagai isu paling penting. Padahal, tidak semua isu viral punya kedalaman substansi. Namun, karena perhatian publik terfokus ke situ, institusi terpaksa merespons agar tidak dianggap abai. Inilah bagaimana ruang digital mengatur agenda lembaga formal, bukan sebaliknya.
Dalam jangka panjang, ketimpangan ritme ini dapat mengganggu kualitas diskursus publik. Masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang mendesak dan informasi yang sekadar menarik perhatian. Institusi makin sulit menjelaskan fakta dengan tenang karena publik sudah terlanjur emosional. Media pun terdorong mengikuti arus viral daripada mendorong isu yang benar-benar penting. Agenda publik akhirnya menjadi hasil kompetisi antara fakta dan sensasi.
Untuk menghadapi situasi ini, institusi perlu memahami bahwa keterlambatan sekecil apa pun dapat mengubah total arah agenda publik. Respons cepat bukan berarti informasi mentah, tetapi kehadiran dini yang mengisi ruang kosong sebelum spekulasi membesar. Institusi perlu menyesuaikan struktur komunikasi agar tidak hanya bergantung pada pernyataan resmi yang panjang dan tidak menarik.
Mereka perlu menyampaikan langkah awal, konteks awal, dan memperbarui informasi secara bertahap. Transparansi semacam ini membantu publik merasa bahwa institusi hadir dan dapat dipercaya.
Pada saat yang sama, publik juga perlu menyadari bahwa kecepatan bukan jaminan kebenaran. Isu viral sering kali hanya puncak dari persoalan yang jauh lebih kompleks. Kita hidup di era ketika perhatian mudah terseret ke sana ke mari oleh agenda digital yang tidak selalu relevan dengan kepentingan publik. Mengembalikan keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan ketenangan adalah tantangan besar bagi demokrasi komunikasi hari ini.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita hadapi bersama adalah apakah kita ingin hidup dalam ekosistem informasi yang diatur oleh fakta atau oleh sensasi. Selama ritme institusi dan ritme publik tidak sejalan, agenda perbincangan akan terus dipimpin oleh yang paling cepat, bukan oleh yang paling benar. Tantangannya bukan hanya bagi institusi, tetapi juga bagi publik yang perlu belajar kembali memberi ruang pada proses verifikasi sebelum membentuk opini.
Informasi yang baik bukan hanya tepat waktu, tetapi juga tepat makna. Dan untuk mencapainya, kita perlu menata ulang cara kita merespons setiap isu viral yang melintas di layar. (*/ Cep)
Ikhsan Ababil, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Korporat Universitas Paramadina.